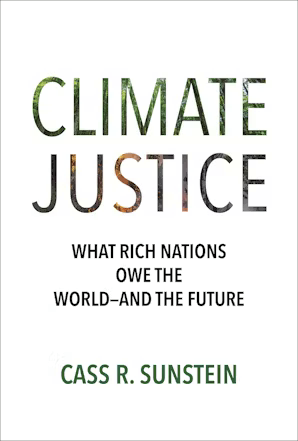 Oleh: Jalal
Oleh: Jalal
Urgensi Memahami Keadilan Iklim
Sebagai seorang yang mengamati dengan lekat isu-isu keberlanjutan di Indonesia, saya menyaksikan langsung betapa penting dan mendesaknya penegakan keadilan iklim. Keadilan iklim bukan lagi sekadar wacana yang dibincangkan secara terbatas oleh para akademisi atau aktivis, melainkan realitas pahit yang dirasakan oleh jutaan jiwa di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kita hidup di bawah bayang-bayang ancaman yang semakin nyata—banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, badai yang merusak, dan kenaikan permukaan air laut yang mengikis daratan—dan seakan tak pernah ‘lupa’ menempati headline di media massa dan viral di media sosial. Ironisnya, dampak-dampak ini justru paling parah menimpa masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Gegara menyaksikan itu semua di lapangan, kekecewaan mendalam seringkali menyelimuti benak dan hati ketika melihat respons negara-negara maju yang terkesan lamban, tidak proporsional, bahkan jahat, terhadap tuntutan keadilan iklim yang telah lama diserukan.
Saya membaca buku Climate Justice: What Rich Nations Owe the World—and the Future karya Cass R. Sunstein—profesor hukum di Universitas Harvard, pengacara lingkungan, sekaligus ekonom perilaku—ini hadir di tengah kegelisahan tersebut. Ia dengan jernih menawarkan pemikirannya yang komprehensif dan mendalam tentang apa saja dan sebesar apa sebenarnya negara-negara kaya berutang kepada dunia gegara dampak iklim mereka. Karena buku ini, mungkin ia kini menjadi suara terpenting dari negara maju yang bekerja memerkuat argumen bagi hak-hak negara berkembang dalam menghadapi krisis ini iklim ini—sebuah krisis yang mereka tidak ciptakan, namun harus mereka tanggung bebannya. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan bukan hanya tentang kerusakan lingkungan, tetapi juga tentang ketidakadilan moral dan ekonomi yang mendasarinya, serta bagaimana kita dapat melangkah maju menuju solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Memahami keadilan iklim adalah langkah awal untuk menuntut tindakan nyata dan memastikan bahwa beban serta manfaat upaya iklim dibagi secara merata, sesuai dengan prinsip common but differentiated responsibilities.
Tujuh Bab yang Mencerahkan
Sunstein memulai bukunya dengan menekankan bahwa krisis iklim menciptakan penderitaan konkret berupa kematian, penyakit, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, hingga rasa takut terus-menerus pada korbannya. Ia langsung menyatakan bahwa negara-negara miskin jauh lebih rentan, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi jauh lebih kecil. Amerika Serikat disebut sebagai penyumbang historis terbesar, sementara Tiongkok adalah penyumbang tahunan terbesar saat ini. Sunstein berpendapat bahwa setiap orang harus dihitung secara setara, di mana pun dan kapan pun mereka hidup—sebuah klaim yang ia sandarkan pada utilitarianisme John Stuart Mill.
Bab pertama, Climate Change Cosmopolitanism, membahas apakah suatu negara harus memerhitungkan dampak emisi gas rumah kacanya terhadap orang-orang di negara lain saat memutuskan untuk mengurangi emisinya. Sunstein menolak pandangan nasionalistik yang hanya berfokus pada kerugian domestik, dan berargumen mendukung kosmopolitanisme perubahan iklim. Ia menyajikan empat argumen utama untuk penggunaan “angka global” dalam menghitung social cost of carbon (SCC), yang merupakan nilai moneter dari kerusakan yang disebabkan oleh satu ton emisi karbon: Pertama, Argumen Epistemik: Sulit untuk secara akurat mengidentifikasi kerugian murni domestik, sehingga angka global memberikan dasar yang lebih masuk akal. Kedua, Argumen Keterkaitan: Dunia saling terhubung, dan emisi domestik AS dapat merugikan warga negara AS yang tinggal di luar negeri serta menyebabkan kerugian ekonomi dan lainnya melalui efek berjenjang pada negara-negara lain. Ketiga, Argumen Kosmopolitan Moral: Negara-negara harus mempertimbangkan kerugian yang mereka sebabkan pada non-warga negara karena alasan moral yang kuat, sejalan dengan golden rule dan utilitarianisme. Terakhir, Argumen Resiprositas: Jika setiap negara hanya menggunakan angka domestik, semua negara akan menderita. Penggunaan angka global oleh semua negara akan menguntungkan semua pihak, termasuk AS, dan berfungsi sebagai insentif untuk kerja sama internasional dalam mengatasi dilema narapidana iklim.
Sunstein mengakui kerumitan dalam menerapkan angka global, terutama kekhawatiran tentang free-riding, tetapi ia menyimpulkan bahwa kepemimpinan AS dalam menggunakan angka global dapat membentuk norma dan mendorong negara lain untuk mengikuti, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Ia mengutip contoh negara-negara seperti Kanada, Prancis, dan Swedia yang telah mengadopsi angka global atau yang mendekatinya ketika merumuskan kebijakan iklim mereka.
Rich Nations, Poor Nations, bab kedua, secara mendalam membahas isu keadilan distributif dan korektif antara negara kaya dan miskin. Sunstein membandingkan situasi ini dengan Kanada yang menciptakan energi baru yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan negara-negara di Afrika Tengah. Ia menekankan bahwa meskipun Tiongkok adalah penghasil emisi tahunan terbesar saat ini, Amerika Serikat tetap menjadi kontributor terbesar terhadap stok gas rumah kaca yang ada di atmosfer secara historis. Ini memunculkan pertanyaan tentang apakah AS berutang kompensasi kepada negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sebuah konsep yang mendasari ide loss and damage fund.
Sunstein membahas tantangan dalam menerapkan konsep keadilan korektif (ganti rugi atas kesalahan masa lalu) dan keadilan distributif (redistribusi sumber daya dari yang kaya ke yang miskin) pada skala antarnegara. Ia mengakui bahwa negara bukanlah individu, sehingga konsep “pelaku” dan “korban” menjadi kabur. Orang-orang yang bertanggung jawab atas emisi historis sudah meninggal, dan generasi saat ini mungkin tidak secara langsung diuntungkan oleh tindakan masa lalu tersebut. Selain itu, Sunstein juga memertimbangkan bahwa aktivitas industri negara-negara maju di masa lalu juga memberikan manfaat global melalui inovasi dan produk. Meskipun demikian, Sunstein menyimpulkan bahwa argumen keadilan korektif tetap relevan sebagai bentuk rough justice, mengingat negara-negara kaya memang telah membebankan risiko serius pada negara-negara miskin.
Di bab ini dia juga mendiskusikan prinsip common but differentiated responsibilities dari PBB, yang berargumen bahwa kewajiban suatu negara harus didasarkan pada tanggung jawabnya atas perubahan iklim dan kapasitasnya untuk mengurangi emisi. Negara-negara berkembang seringkali berpendapat bahwa prioritas utama mereka adalah meningkatkan standar hidup warganya, dan mereka memerlukan bantuan finansial serta teknologi dari negara-negara kaya. Sunstein secara kuat mendukung redistribusi sumberdaya dari negara-negara kaya ke miskin sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan global dan mencapai keadilan.
Bab ketiga, Future Generations, mendiskusikan bagaimana biaya dan manfaat tindakan iklim harus diperlakukan secara lintas-generasi. Sunstein menjelaskan isu teknis namun etis yang sentral: discounting—yang berarti bahwa manfaat di masa depan dinilai lebih rendah dibandingkan manfaat yang sama di masa kini. Perubahan kecil dalam tingkat diskonto dapat secara dramatis mengubah estimasi biaya perubahan iklim dan manfaat mitigasi. Sunstein menjelaskan bahwa kaum positivis mendiskon berdasarkan tingkat pengembalian pasar dan melihatnya sebagai opportunity cost, sementara kaum etis berargumen untuk netralitas antargenerasi, di mana kesejahteraan generasi mendatang tidak boleh didiskon ‘hanya’ karena mereka hidup di masa depan.
Sunstein di satu sisi setuju dengan kaum etis tentang netralitas antargenerasi (kesejahteraan orang yang lahir tahun 2050 tidak kurang penting daripada yang lahir tahun 2010), tetapi juga setuju dengan kaum positivis bahwa uang harus didiskon untuk menghindari pemborosan sumberdaya masa sekarang. Argumen utamanya adalah bahwa diskonto uang memastikan sumberdaya diinvestasikan secara efisien untuk manfaat generasi mendatang. Ia juga memerkenalkan kerumitan seperti ketidakpastian (yang menyarankan tingkat diskonto yang lebih rendah) dan masalah bahwa generasi mendatang mungkin lebih kaya, sehingga nilai marginal konsumsi mereka lebih rendah. Sunstein menyimpulkan bahwa tingkat diskonto harus didasarkan pada perkiraan suku bunga pasar, sekitar 1.5-2 persen, dan bahwa tujuan diskonto adalah memandu pilihan projek yang efisien, bukan untuk menentukan kewajiban etis kita kepada masa depan.
Bab keempat, Valuing Life: Who Wins, Who Loses?, membahas pertanyaan sulit tentang bagaimana pemerintah harus menilai nyawa manusia dalam kebijakan iklim, terutama dalam konteks risiko Value of Statistical Life (VSL). Sunstein menjelaskan bahwa VSL adalah alat yang digunakan untuk mengukur kesediaan membayar untuk mengurangi risiko kematian, bukan untuk menilai nyawa individu. Di AS, VSL yang digunakan secara umum adalah sekitar $12 juta. Namun, Sunstein mengkritik praktik EPA yang menyesuaikan VSL berdasarkan pendapatan per kapita negara, yang secara implisit berarti nyawa di negara miskin dinilai lebih rendah.
Ia kemudian mengidentifikasi lima masalah hipotetis untuk mengeksplorasi bagaimana VSL yang seragam atau berbeda memengaruhi orang miskin dan kaya dalam konteks subsidi versus regulasi. Sunstein berargumen bahwa dalam kasus subsidi, VSL yang seragam dan tinggi (misalnya, $12 juta) cenderung menguntungkan orang miskin karena mereka menerima “subsidi dalam bentuk barang” berupa pengurangan emisi yang lebih besar dari negara-negara maju. Namun, dalam kasus regulasi di mana orang miskin menanggung sebagian besar biayanya, VSL yang seragam dapat merugikan mereka. Ia menyimpulkan bahwa penggunaan VSL yang disesuaikan kekayaan—misalnya VSL rendah untuk negara miskin—dalam perhitungan SCC akan menjadi bentuk subsidi besar yang tidak adil. Dari diskusi ini, Sunstein jelas mendukung VSL yang seragam secara global untuk tujuan penetapan harga karbon, demi keadilan.
Bab kelima, Adaptation, beralih dari mitigasi ke pentingnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Sunstein menggunakan contoh standar kebakaran hutan di California untuk menunjukkan bagaimana kebijakan adaptasi dapat secara signifikan mengurangi kerugian. Sunstein menekankan bahwa adaptasi sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ia menguraikan berbagai alat kebijakan untuk memromosikan adaptasi: insentif (bantuan finansial, teknis), regulasi (aturan bangunan tahan api), dan dorongan (nudging, seperti penyediaan informasi). Sunstein juga menyoroti kerumitan etika adaptasi, khususnya masalah valuasi dan keadilan distributif. Misalnya, subsidi adaptasi mungkin menghasilkan manfaat moneter yang lebih tinggi di komunitas kaya daripada di komunitas miskin, meskipun manfaat kesejahteraan riil (misalnya, nilai rumah) mungkin setara atau lebih besar di komunitas miskin. Ia mendukung prioritisasi kesejahteraan mereka yang paling tidak beruntung, bahkan jika itu berarti mengorbankan sedikit kesejahteraan agregat. Sunstein juga membahas masalah risiko probabilitas rendah dan ketidakpastian dalam perencanaan adaptasi. Ia menekankan perlunya memberikan informasi yang jelas kepada komunitas tentang risiko dan cara mengatasinya, serta menyediakan sumberdaya dan bantuan teknis.
Pada bab keenam, Consumers, Sunstein mengeksplorasi peran pilihan konsumen dalam krisis iklim dan bagaimana kebijakan dapat dibentuk untuk memerbaiki pilihan tersebut. Ia meneliti bagaimana intervensi seperti laporan energi yang dipergunakan di rumah, label minuman manis, dan label kalori memengaruhi perilaku konsumen. Ia menyimpulkan bahwa intervensi memiliki efek hedonik, bervariasi antar-populasi, sehingga efek rata-rata mungkin tidak menggambarkan keseluruhan cerita secara memuaskan.
Sunstein kemudian memerkenalkan konsep Choice Engines, sebuah teknologi daring yang menawarkan opsi atau default yang disesuaikan berdasarkan preferensi dan bias perilaku konsumen. Mesin ini bertujuan untuk mengatasi bias perilaku seperti present bias, di mana konsumen terlalu mementingkan biaya dan manfaat jangka pendek daripada jangka panjang. Ia berpendapat bahwa mesin ini dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan mereka sendiri (mengatasi internalitas) sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca (mengatasi eksternalitas). Sunstein juga membahas justifikasi kebijakan seperti standar efisiensi bahan bakar dan energi, yang dapat mengurangi internalitas dan eksternalitas—meskipun ia nyatakan mungkin kurang efisien dibandingkan pajak karbon. Ia menekankan perlunya guardrails untuk mencegah mesin yang agar tidak manipulatif dan bias.
Bab terakhir, Epilog, merangkum sepuluh kesimpulan utama Sunstein, yang mengulang argumen-argumen kunci dari setiap bab. Secara keseluruhan, Sunstein menegaskan perlunya penggunaan angka global untuk biaya sosial karbon, redistribusi kekayaan dari negara kaya ke miskin, prinsip netralitas antargenerasi, dan valuasi nyawa yang konsisten dalam konteks kebijakan iklim. Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi dan peran pilihan konsumen serta teknologi seperti Choice Engines dalam mengatasi tantangan iklim. Epilog diakhiri dengan pengakuan bahwa meskipun fokusnya adalah pada pertanyaan teoretis tentang “benar dan salah”, ia juga memahami adanya batasan terhadap apa yang bersedia dilakukan oleh negara-negara kaya. Namun, ia menekankan bahwa penilaian etika adalah latar belakang penting bagi para pejabat publik dan negosiator, yang dapat berfungsi sebagai North Star dalam upaya global mengatasi krisis iklim dan dampaknya.
Timbangan dan Harapan
Bagi saya, karya terbaru Sunstein ini menghadirkan analisis yang mendalam dan provokatif mengenai salah satu isu paling pelik yang sedang kita hadapi. Kekuatan utamanya terletak pada kerangka etika yang kuat dan koheren yang ia bangun, terutama penekanannya pada kosmopolitanisme moral dan netralitas antargenerasi. Sunstein dengan berani menantang pandangan nasionalistik sempit yang mendominasi perdebatan kebijakan iklim, dan secara persuasif berargumen bahwa kerugian yang disebabkan oleh emisi di satu negara harus diperhitungkan secara penuh, di mana pun orang yang terkena dampak itu hidup. Argumen resiprositas yang ia kemukakan—yakni bahwa penggunaan angka SCC global oleh negara maju akan mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama dan menguntungkan semua pihak—adalah sebuah perspektif strategis di hadapan kerumitan isu iklim.
Pendekatan Sunstein yang memadukan filsafat etis dengan analisis ekonomi dan kebijakan juga patut diacungi jempol. Ia tidak ragu untuk masuk ke dalam detail teknis seperti tingkat diskonto dan VSL, namun berhasil menyajikannya dengan cara yang menjelaskan implikasi etisnya yang mendalam. Kemampuannya untuk membongkar asumsi di balik model-model ekonomi konvensional dan menyoroti bias inherennya adalah kontribusi luar biasa penting. Misalnya, kritik terhadap praktik penyesuaian VSL berdasarkan pendapatan per kapita adalah argumen yang sangat relevan dan mendasar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang seringkali merasa nyawa warganya dinilai lebih rendah oleh mekanisme global. Pengenalan konsep rough justice untuk mengakui klaim keadilan korektif dari negara-negara miskin—meskipun ada tantangan dalam identifikasi pelaku dan korban secara presisi—menunjukkan pragmatisme Sunstein tanpa mengorbankan prinsip moral. Analisisnya tentang adaptasi, yang seringkali terpinggirkan oleh fokus pada mitigasi, juga merupakan kekuatan, menyoroti strategi konkret dan tantangan distribusinya. Terakhir, wawasannya tentang peran pilihan konsumen dan Choice Engines adalah ide yang inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, meskipun jelas memerlukan pengawasan yang ketat.
Namun, jelas masih ada beberapa ruang untuk perbaikan yang saya deteksi. Meskipun Sunstein mengakui kompleksitas dan tantangan empiris dalam menerapkan konsep-konsep seperti keadilan korektif dan distributif antarnegara, terkadang pembahasannya masih terasa agak abstrak dari sudut pandang pembaca dari negara berkembang seperti saya. Misalnya, ia berargumen kuat untuk redistribusi kekayaan, tetapi masih kurang mendetail mengenai mekanisme implementasinya. Mengingat sejarah kegagalan transfer teknologi dan janji pendanaan iklim yang tidak kunjung terpenuhi, buku ini sesungguhnya bisa diperkaya dengan analisis yang lebih mendalam tentang hambatan-hambatan politik dan institusional yang menghalangi implementasi keadilan iklim di dunia nyata.
Pembahasan mengenai peran negara-negara berkembang itu sendiri dalam mendorong keadilan iklim, selain sebagai penerima kompensasi atau bantuan, jelas juga bisa diperdalam. Bagaimana negara-negara berkembang dapat secara proaktif membentuk narasi, membangun aliansi, dan menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk menekan negara-negara maju? Selain itu, sementara Sunstein membahas peran AI melalui Choice Engines dalam mengubah perilaku konsumen, eksplorasi lebih lanjut tentang potensi teknologi ini dalam mendukung adaptasi di negara berkembang, misalnya melalui sistem peringatan dini yang cerdas atau platform berbagi pengetahuan adaptasi, akan menjadi tambahan yang menarik. Terakhir, sentuhan lebih banyak tentang bagaimana budaya dan nilai lokal di negara-negara yang sangat rentan memandang dan merespons krisis iklim agaknya akan memberikan nuansa yang lebih kaya pada argumen kosmopolitan Sunstein.
Membaca buku ini memberikan harapan sekaligus memicu refleksi mendalam. Saya sangat berharap buku ini dapat dibaca oleh para pemimpin negara maju maupun berkembang. Bagi para pemimpin negara maju, semoga buku ini menjadi pengingat yang kuat akan tanggung jawab historis dan moral mereka untuk mengatasi krisis iklim yang sebagian besarnya mereka sebabkan. Ini sesungguhnya bukanlah tentang kesukarelaan atau rasa kasihan, melainkan tentang kewajiban etis dan strategis demi masa depan bersama. Sudah saatnya untuk melampaui retorika dan mewujudkan komitmen nyata dalam bentuk pengurangan emisi yang ambisius, transfer teknologi yang adil, dan pendanaan adaptasi yang memadai.
Bagi para pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia, buku ini menawarkan penguatan argumen dan wawasan untuk terus menuntut keadilan iklim dengan basis moral dan ekonomi yang kuat. Kita perlu secara kolektif berpegang pada prinsip-prinsip ini dalam setiap negosiasi dan kebijakan, memastikan bahwa pembangunan yang kita perjuangkan adalah pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Hanya dengan kesadaran yang mendalam akan keadilan iklim, dan kemauan untuk berkolaborasi secara tulus, kita dapat mewujudkan mitigasi dan adaptasi yang efektif. Masa depan bumi ini, dan seluruh isinya, bergantung pada kemampuan kita untuk bertindak bersama, bukan sebagai entitas yang bersaing, apalagi saling menghancurkan, melainkan sebagai satu keluarga besar yang berbagi satu rumah bernama Bumi. Oleh karenanya, saya juga berharap buku ini—dan karya-karya lainnya dalam tema keadilan iklim—dapat menjadi katalisator bagi perubahan transformatif yang sangat kita butuhkan sesegera mungkin.
–##–






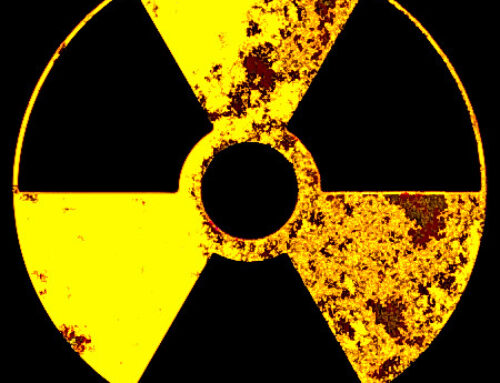
Leave A Comment