Oleh: Jalal, Noviansyah Manap & Zainal Abidin
Institusi mana yang paling tidak dipercaya rakyat Indonesia? Survei Indikator Politik yang terbit akhir Januari 2025 lalu menunjukkan: partai politik, DPR dan Kepolisian Republik Indonesia adalah 3 yang paling rendah tingkat kepercayaan masyarakatnya. Kebetulan, 3 institusi ini pula yang sedang jadi sasaran kedongkolan, kemarahan, hingga amukan massa di akhir Agustus 2025.
Tapi kita tahu bahwa demokrasi adalah sistem politik yang paling bisa diandalkan untuk kita semua bisa berkonsensus soal hal-hal yang jadi hajat hidup orang banyak. Jadi, ketika banyak orang berteriak bubarkan DPR, kami tak setuju. Pak Mahfud MD menjelaskan dengan sangat baik tentang mengapa kita memerlukan institusi ini, walau isi dan kinerjanya kini sungguh menyebalkan, “sampai ke level dewa.”
Kalau kita butuh DPR, juga butuh Polri, tapi mereka sedang tidak baik-baik saja, mereka perlu direformasi, atau lebih tepatnya diregenerasi agar kompatibel dengan tujuan masa depan. Tapi kami yakin, kita sesungguhnya tak butuh parpol. Kita butuh wakil rakyat, tapi mekanisme pemilihan lewat parpol, apalagi pemilihan langsung dalam Pemilu bukanlah esensi dari keterwakilan rakyat di DPR.
Bayangkan dunia politik tanpa kampanye yang menguras dana miliaran buat setiap kandidatnya, tanpa iklan dan berita televisi berjam-jam yang penuh janji manis, dan tanpa debat panas yang lebih mirip pertunjukan daripada diskusi serius. Tidak ada lagi klaim “saya adalah suara rakyat” yang terdengar hampa karena kandidatnya justru berasal dari lingkaran elit yang sama dan “lu lagi, lu lagi“.
Kami mendiskusikan kemungkinan itu lewat grup WA, lalu di warung sate favorit kami. Kami mendapati sebuah buku terbitan tahun lalu Lottocracy: Democracy without Elections oleh Alexander Guerrero yang mengajak kita juga membayangkan dunia seperti itu. Lebih jauh daripada membayangkan, dia menganalisa dan menyarankan, dengan nada serius dan logis, bahwa mungkin saatnya kita berhenti memilih wakil rakyat via partai politik, dan mulai mengundinya secara acak saja. Persis seperti mekanisme yang kami bayangkan.
Guerrero bukan orang sembarangan. Dia adalah profesor filsafat politik di Universitas Rutgers. Dia juga diakui sebagai pakar etika plus epistemologi. Jadi, dia adalah orang yang pas untuk membantu kami untuk lebih jauh lagi membayangkan lottokrasi, alias demokrasi tanpa parpol ini.
Lottokrasi—dari kata lot, alias undian—adalah ide yang sekarang terdengar radikal, tapi sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum era pemilu modern seperti, Athena Kuno sudah menerapkannya: juri, pejabat publik, bahkan anggota dewan dipilih secara acak. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa kekuasaan harus dipegang oleh rakyat biasa, bukan hanya oleh elit yang punya uang banyak, nama besar, apalagi syahwat politik yang menggelegak. Dan Guerrero menyatakan: mungkin mereka lebih benar daripada sistem perwakilan kita sekarang.
Demokrasi Kita Sedang Sakit
Sebelum menawarkan obat, Guerrero melakukan diagnosis yang tajam: demokrasi elektoral modern sedang dalam kondisi sakit kronis. Bukan hanya di negara-negara otoriter, tapi juga di negara-negara yang dianggap maju. Mengapa?
Pertama, kita semua terlalu sibuk—dan terlalu buta informasi. Pemilih rata-rata tidak punya waktu untuk memahami pentingnya kebijakan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, reformasi pajak, atau sistem kesehatan yang rumit. Media massa, alih-alih membantu, justru menyajikan politik sebagai hiburan: siapa yang lebih keren, lebih galak, atau lebih gemoy? Akibatnya, pemilih memilih berdasarkan citra, emosi, atau bias ideologis—bukan berdasarkan kebijakan yang rasional.
Kedua, yang terpilih sekarang jelas bukan gambaran rakyat sama sekali. Parlemen dan pemerintahan dipenuhi oleh orang-orang kaya, pengusaha, pengacara, dan politikus karier—kelompok yang sangat kecil dan tidak representatif blas. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya tergopoh-gopoh naik angkutan umum atau motor sebelum jam 6 pagi, atau khawatir tagihan listrik naik. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali jauh dari realitas kehidupan rakyat kebanyakan.
Ketiga, sistem ini rentan dimainkan. Uang dan lobi bisa dengan mudah membentuk kebijakan. Kampanye politik yang mahal membuat hanya mereka yang punya atau punya akses ke sumberdaya besar yang bisa bersaing, termasuk dengan melacurkan diri kepada para oligarkh. Belum lagi, politikus yang takut tidak terpilih lagi cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang populis—seperti janji turunkan pajak atau naikkan gaji PNS—tapi mengabaikan isu besar seperti utang negara atau krisis iklim.
Lebih pelik lagi, partai politik bukan hanya menentukan siapa yang boleh maju, tetapi juga bisa sewaktu-waktu menarik mandat yang telah diberikan rakyat. Kandidat tanpa modal besar hampir tidak pernah mendapat kesempatan, kecuali jika mereka mau tunduk pada mekanisme mahar politik atau patronase. Dan ketika sudah terpilih pun, posisi mereka kerap rapuh—bisa digeser oleh elit partai yang lebih berkuasa, meski rakyat sudah memberi suara. Fenomena ini memerlihatkan bahwa kursi parlemen pada praktiknya lebih sering dipandang sebagai milik partai, bukan amanat publik.
Partai-partai politik hari ini kian menjauh dari hakikatnya sebagai representasi suara rakyat. Dalam praktik pengelolaan internal, banyak partai lebih menyerupai badan usaha milik keluarga, di mana kepemimpinan diwariskan turun-temurun dan keputusan penting ditentukan segelintir orang saja. Dengan feodalisme yang begitu kental, sulit mengharapkan partai benar-benar memerjuangkan kepentingan rakyat banyak. Sebaliknya, yang terjadi adalah reproduksi kekuasaan dan kepentingan oligarkhi politik yang semakin jauh dari kebutuhan masyarakat luas.
Feodalisme politik berpadu mesra dengan oligarkhi bisnis. Para pemilik modal besar bukan lagi sekadar penyokong, melainkan sudah menjadi “mitra strategis” yang ikut mengarahkan jalannya partai. Hubungan mesra antara partai dan oligarkhi bisnis inilah yang membuat kebijakan publik sering lebih mencerminkan kepentingan pemodal daripada kepentingan rakyat banyak.
Lottokrasi: Bukan Revolusi, Tapi Penataan Ulang (Reset)
Lalu, solusinya? Hancurkan demokrasi? Tentu tidak. Tapi reset sistem ini dari akarnya. Ganti pemilu lewat parpol dengan undian—tapi bukan undian sembarangan. Ini adalah sistem yang terstruktur, terencana, dan didesain untuk menghasilkan keputusan yang lebih bijak, adil, dan representatif.
Bayangkan parlemen tidak lagi terdiri dari satu badan besar yang harus tahu segalanya, tapi terbagi menjadi 20 kelompok kecil, masing-masing fokus pada satu isu: Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Pertanian, Pajak, dan seterusnya. Setiap kelompok ini disebut oleh Guerrero sebagai SILL alias Single-Issue Legislative Legislature, terdiri dari 450 warga biasa yang dipilih secara acak untuk masa jabatan tiga tahun. Setiap tahun, 150 anggota diganti—jadi tidak ada yang bisa “berkuasa” terlalu lama.
Mereka bukan langsung bikin undang-undang. Mereka belajar dulu. Di awal masa jabatan, mereka dikumpulkan, diberi paparan dari para ahli, bertemu dengan aktivis, mendengar langsung keluhan dan bentuk-bentuk masukan masyarakat lainnya, bahkan turun ke lapangan. Mereka diajak diskusi intensif, debat ide, dan merumuskan solusi. Proses ini disebut fase pembelajaran, dan inilah yang membuat lottokrasi bukan sekadar undian lalu langsung bikin keputusan, tapi sistem yang menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan kolektif. Wisdom of the crowds, begitu dia biasa disebut.
Kami sendiri tak berpikir bahwa jumlah dan jangka waktu tugasnya harus seperti yang diajukan Guerrero. Kami memikirkan mekanisme penggantian lewat penilaian kinerja oleh masyarakat, di mana 20% terbawah diganti setiap tahunnya. Dan ini kami pikirkan lantaran jangka waktu yang ada di benak kami memang masih 5 tahunan.
Mengapa Acak Justru Lebih Adil?
Kita sering berpikir acak itu berarti kacau. Tapi Guerrero menunjukkan, justru seleksi acak bisa lebih adil dan cerdas dibanding pemilihan. Pertama, representasi demografis. Parlemen acak akan mencerminkan masyarakat sebenarnya: ada ibu rumah tangga, petani, buruh, pensiunan, penyandang disabilitas, minoritas etnis—semua punya peluang sama. Dalam sistem pemilu, mereka hampir mustahil menang. Dalam lottokrasi, mereka tidak hanya hadir, tapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kami berpendirian bahwa proporsi yang minoritas perlu secara sengaja ditingkatkan. Mereka yang berasal dari agama dan suku minoritas, dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perlu ditingkatkan proporsinya sebagai wakil rakyat.
Kedua, kebebasan dari tekanan politik. Karena tidak perlu mencari suara, semua anggota SILL tidak takut membuat keputusan yang tidak popular tapi benar. Mereka tidak perlu menjilat kepentingan bohir atau partainya. Mereka bisa berkata, “Ya, kita harus naikkan cukai rokok, meskipun itu tidak enak bagi perokok, karena ini demi kesehatan publik.” Atau, “Pajak karbon harus terus naik supaya rakyat tak terus-terusan dihajar banjir dan kekeringan.” Dan mereka bisa melakukannya tanpa takut dihukum di pemilu berikutnya—karena memang tidak ada pemilu berikutnya!
Ketiga, lebih rasional dan transparan. Diskusi berlangsung di ruang tertutup yang terstruktur, bukan di panggung debat yang penuh drama. Tidak ada ruang bagi kampanye hitam atau hoaks yang viral. Keputusan diambil berdasarkan data, bukti, dan pertimbangan moral—bukan emosi atau identitas kelompok.
Bukan Revolusi, Tapi Eksperimen Sosial
Tentu, mengganti seluruh sistem demokrasi dalam semalam adalah hal yang tidak realistis—dan berisiko. Maka Guerrero menyarankan pendekatan inkremental: coba dulu di level lokal. Kota kecil bisa membentuk majelis warga acak untuk merancang kebijakan pengelolaan sampah atau transportasi massal. Sekolah atau perusahaan bisa menerapkan lottokrasi dalam pengambilan keputusan internal. Di Kanada dan Mongolia, eksperimen serupa menunjukkan hasil-hasil yang menjanjikan. Kami sendiri, lantaran dalam pekerjaan kerap bertemu dengan para petani, nelayan, masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, percaya sepenuhnya bahwa mereka cerdas dan bijaksana. Dalam banyak kesempatan, kami dibuat terkagum-kagum, kalau bukan malah termehek-mehek, pada pemikiran mereka. Mereka jelas jauh lebih pantas jadi wakil rakyat dibandingkan ‘tokoh’ yang punya patung Iron Man atau yang tak becus mengurus kucing-kucingnya itu.
Kita perlu melakukan eksperimen sosial ini di daerah-daerah. Langkah-langkah kecil ini penting untuk membangun kepercayaan. Orang akan lebih percaya pada sistem yang mereka lihat berhasil, bukan yang hanya diomongkan filsuf politik—atau obrolan tiga sahabat yang hobi mengudap durian dan nyate yang menghasilkan tulisan ini. Dan yang paling penting, sistem ini tidak menghapus partisipasi warga—malah membukanya selebar mungkin. Anda tidak terpilih jadi anggota SILL? Tidak masalah. Anda tetap bisa mengajukan petisi, mengorganisasi kampanye damai untuk mendukung isu tertentu, menjadi narasumber pada proses deliberatif, atau mengajukan kritik atas keputusan mereka. Yang berubah hanyalah siapa yang membuat keputusan akhir.
Di luar yang dibahas Guerrero, kami juga merundingkan soal pembatasan gaji (dibatasi maksimal 3 atau 4 kali lipat GDP per kapita—yang akan menjadi menarik bagi majoritas masyarakat Indonesia tapi akan membuat mereka yang tajir tak bakal meneteskan liur) dan fasilitas, pemilihan dan kompensasi untuk pakar yang mendampingi mereka, guardrails agar tak ada konflik kepentingan, juga sanksi ekstra-keras bila tertangkap korupsi.
Mungkin Sudah Saatnya Kita Berhenti Mencoblos Wakil Rakyat
Lottokrasi jelas bukan solusi sempurna, lantaran memang tidak ada sistem politik yang sempurna. Tapi ide ini menantang kita semua untuk berpikir ulang: apakah pemilu benar-benar cara terbaik untuk memilih wakil rakyat? Atau justru telah menjadi alat untuk memertahankan status quo, di mana hanya segelintir orang dengan sumberdaya luar biasa besar saja yang bisa menang?
Dengan lottokrasi, demokrasi bisa kembali ke akarnya: pemerintahan oleh rakyat, bukan oleh selebritas, pengacara, atau taipan. Ini bukanlah ide untuk menghancurkan demokrasi, tapi menyelamatkannya dari kegagalan sistematis yang sudah terlalu lama kita abaikan, padahal semua kesalahan itu tersaji di depan mata kita semua.
Jadi, mungkin—hanya mungkin—masa depan demokrasi bukan di tangan pemilih, tapi di tangan mereka yang terpilih secara acak namun difasilitasi sepenuhnya untuk bisa bekerja secara serius.
Dan, kami membayangkan, kalau benar-benar yang berkantor di Senayan itu adalah para wakil yang sepenuhnya mencerminkan rakyat Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap mereka, akan persis seperti kepercayaan terhadap diri kita sendiri.
Indonesia, 3 September 2025






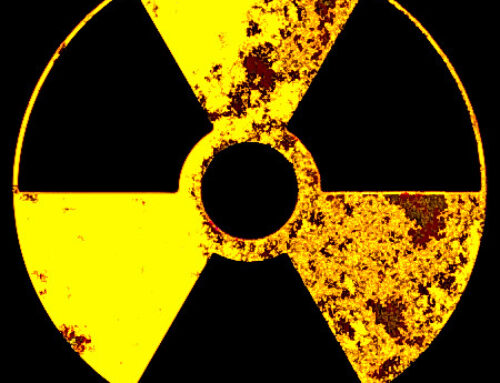
Kasih aja gaji UMR, langsung mengundurkan diri mereka