Oleh: Jalal
Perdebatan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia selalu muncul dan tenggelam, seperti halnya ombak di pantai yang tak pernah berhenti. Setiap kali harga energi fosil merangkak naik atau target penurunan emisi kembali menjadi sorotan global, wacana nuklir mengemuka sebagai solusi yang dianggap elegan: listrik stabil, emisi karbon rendah, dan teknologi maju yang dapat mengangkat citra atau bahkan reputasi negara. Itu adalah butir-butir yang diangkat oleh beberapa jurnalis yang mencegat saya untuk diskusi dadakan di akhir minggu lalu.
Tetapi di balik beragam alasan pro-nuklir yang agaknya dihapal oleh para jurnalis itu—menurut hemat saya—tersimpan sederet pertanyaan mendasar yang belum terjawab tuntas: Sejauh mana kita siap mengelola risiko keamanan yang unik pada nuklir? Apakah biaya dan waktu yang dibutuhkan sepadan dengan manfaatnya? Bagaimana dampaknya terhadap pembangunan energi terbarukan yang justru belum kita maksimalkan? Dan, mungkin yang paling penting, apakah pilihan ini bijak untuk konteks ekonomi, sosial, dan politik Indonesia?
Konteks saat ini, terutama wacana untuk memiliki PLTN komersial 250 megawatt di tahun 2032, membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin relevan. Permintaan listrik nasional cenderung terus meningkat, sementara bauran energi kita masih didominasi oleh batubara yang menyumbang emisi gas rumah kaca besar. Sementara, komitmen iklim Indonesia di bawah Perjanjian Paris sesungguhnya menuntut penurunan emisi signifikan pada dekade ini. Dalam kondisi seperti itu, daya tarik nuklir agaknya jelas. Ia menyediakan pasokan daya berkapasitas besar yang stabil tanpa emisi operasional signifikan, dan secara teoretis kini dapat berjalan selama 60 tahun atau lebih. Namun, realitas teknis, institusional, dan finansialnya jauh lebih kompleks daripada sekadar membangun pembangkit.
Bagi saya, faktor keamanan adalah batu ujian pertama yang tidak bisa dihindari. Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik, yang berarti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik adalah keniscayaan, bukan sekadar kemungkinan. Jepang, negara dengan salah satu standar keamanan nuklir tertinggi, mengalami bencana Fukushima pada 2011 ketika kombinasi gempa besar dan tsunami mematikan sistem pendingin reaktor. Dampaknya meluas: evakuasi ratusan ribu orang, pencemaran radioaktif, kerugian ekonomi luar biasa besar—diperkirakan ‘hanya’ sekitar Rp650 triliun segera setelah kejadian, lalu menjadi sekitar Rp10.300 triliun sebelas tahun kemudian—dan, tentu saja, kejatuhan reputasi nuklir di mata publik.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa bahkan negara dengan sumberdaya teknis sangat tinggi dan regulasi yang kuat pun tidak kebal terhadap kegagalan. Indonesia benar-benar harus jujur berhitung dalam soal ini. Kapasitas pengawasan, pengalaman operasi, dan kesiapan tanggap darurat kita masih jauh di bawah Jepang. BAPETEN memang berperan sebagai regulator nuklir nasional dan telah menjalani evaluasi IAEA, namun mengawasi PLTN komersial memerlukan ratusan tenaga ahli bersertifikat, sistem inspeksi yang harus berjalan 24/7, serta infrastruktur tanggap darurat yang belum pernah diuji untuk skala sebesar itu.
Selain risiko langsung dari operasi reaktor, persoalan limbah radioaktif menjadi isu yang tidak kalah rumit. Bahan bakar bekas PLTN mengandung radioisotop yang tetap bisa berbahaya selama ribuan tahun. Beberapa negara seperti Finlandia telah membangun fasilitas penyimpanan akhir dengan deep geological repository, tetapi prosesnya memakan waktu puluhan tahun dan biaya miliaran dolar. Dan Finlandia adalah negara dengan wilayah geologis yang stabil. Indonesia hingga sekarang agaknya belum memiliki strategi final penyimpanan limbah, bahkan untuk limbah tingkat tinggi yang dihasilkan dari reaktor penelitian yang relatif kecil. Tanpa kebijakan limbah yang jelas, termasuk jaminan pendanaan decommissioning—yang diberlakukan untuk industri pertambangan dan migas—serta penyimpanan stabil jangka panjang, memulai projek nuklir berarti mewariskan tanggung jawab yang mahal dan berisiko kepada generasi mendatang.
Penguasaan teknologi juga merupakan tantangan besar. Pembangunan PLTN jelas tidak sekadar soal konstruksi fisik, tetapi benar-benar membangun seluruh ekosistem keahlian yang melibatkan desain, operasi, perawatan, keamanan, hingga daur ulang bahan bakarnya. Vendor internasional biasanya menyediakan teknologi dalam paket lengkap, termasuk pasokan bahan bakar dan layanan teknis, yang berujung pada ketergantungan jangka panjang jika Indonesia tidak terlebih dahulu berhitung matang dan menyiapkan semuanya. Dan, dalam dunia yang semakin terfragmentasi secara geopolitik, ketergantungan ini mengandung risiko strategis. Krisis diplomatik atau gangguan rantai pasok dapat berimbas pada keberlangsungan operasi. Memang, transfer teknologi bisa diupayakan melalui program pendidikan dan kerja sama riset, tetapi pengalaman global menunjukkan bahwa membangun kapasitas domestik yang setara dan mumpuni memerlukan waktu puluhan tahun.
Dari segi biaya, PLTN adalah investasi raksasa yang penuh ketidakpastian. Biaya modal awalnya sangat tinggi, sering kali mencapai miliaran dolar per unit, dan sejarah menunjukkan kecenderungan pembengkakan biaya akibat penundaan dan hal-hal lainnya. Projek Vogtle di Amerika Serikat, misalnya, mengalami penundaan bertahun-tahun—dari yang diperkirakan selesai di tahun 2016 akhirnya menjadi 2024—dan pembengkakan biaya hingga dua kali lipat dari rencana awal—dari USD14 menjadi USD35 miliar. Laporan dari berbagai organisasi terkemuka seperti Lazard dan International Energy Agency menegaskan bahwa, dalam banyak kasus, listrik dari PLTN tetap lebih mahal dibandingkan dari pembangkit surya dan angin, terutama jika memerhitungkan biaya awal dan risiko projek. Nuklir memang bisa kompetitif dalam skenario tertentu, tetapi memerlukan manajemen projek yang luar biasa disiplin dan dukungan kebijakan yang konsisten—dua hal yang sering menjadi titik lemah projek infrastruktur di Indonesia.
Di sisi lain—dan ini yang menurut saya terpenting—Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tenaga surya mencapai 208 gigawatt, tenaga angin 154 gigawatt, tenaga panas bumi lebih dari 23 gigawatt, dan tenaga air 19 gigawatt. Namun realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan kita baru sebagian sangat kecil dari potensi tersebut. Hambatannya—sebagaimana yang sudah sangat kerap disampaikan—bukanlah pada isu teknologi atau sumberdaya alam, melainkan pada kebijakan yang tidak konsisten, mekanisme kontrak yang kurang menarik bagi investor, dan keterbatasan infrastruktur jaringan listrik. Mengalokasikan modal dalam jumlah yang besar untuk PLTN, sementara potensi terbarukan belum dipacu maksimal, agaknya adalah keputusan yang patut dipertanyakan.
Pendukung PLTN sering menekankan bahwa nuklir memberikan pasokan baseload yang stabil, yang penting untuk menyeimbangkan intermitensi terbarukan. Memang benar adanya bahwa PLTN dapat berjalan terus-menerus dengan faktor kapasitas tinggi. Namun kemajuan teknologi penyimpanan energi, jaringan pintar, dan manajemen beban membuat sistem ketenagalistrikan tanpa nuklir kini sudah jauh lebih andal daripada satu dekade lalu. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa kombinasi terbarukan dengan penyimpanan skala besar, pembangkit fleksibel berbahan bakar gas atau biomassa, serta integrasi lintas-wilayah dapat menyediakan listrik yang andal dan rendah karbon tanpa risiko nuklir.
Tetapi ini semua bukan berarti nuklir harus dihapus dari peta jalan energi Indonesia. Justru, opsi ini patut dipertahankan sebagai cadangan strategis jangka panjang, tetapi dengan prasyarat ekstra-ketat. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan bertahap melalui projek percontohan skala kecil, seperti Small Modular Reactor (SMR) yang banyak disarankan oleh pakar, di lokasi yang aman secara geologis dan jauh dari pusat populasi padat. Program ini harus didukung pengawasan regulator yang diperkuat, mekanisme partisipasi publik yang akuntabel dan transparan, dan evaluasi independen pada setiap tahapnya. Keberhasilan projek percontohan semacam ini dapat menjadi landasan pengetahuan dan kepercayaan sebelum melangkah ke projek skala besar yang bakal mengikat Indonesia selama puluhan tahun ke depan.
–##–
Sementara itu, bagi saya, prioritas Indonesia pada dekade ini seharusnya sudah sangat jelas: memaksimalkan potensi energi terbarukan yang sudah ada. Reformasi kebijakan untuk menarik dalam investasi surya, angin, dan panas bumi perlu segera dilakukan, termasuk perbaikan perjanjian pembelian listrik, percepatan pembangunan jaringan, dan insentif untuk teknologi penyimpanan. Setiap rupiah yang diinvestasikan harus diukur dari seberapa cepat ia mengurangi emisi dan dampak lingkungan lainnya di satu sisi; dan meningkatkan keandalan pasokan listrik, juga beragam manfaat sosial dan ekonomi di sisi lainnya. Strategi ini tidak hanya mengurangi risiko teknologi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal, memerkuat industri dalam negeri, dan mendistribusikan manfaat ekonomi lebih merata.
Keputusan untuk membangun PLTN, atau tidak, sesungguhnya adalah keputusan strategis lintas-generasi. Ia akan menentukan arah bauran energi, pola investasi, dan tingkat risiko yang kita wariskan untuk generasi mendatang. Jalan menuju nuklir tidak boleh ditempuh karena dorongan prestise nasional atau klaim keandalan teknologi (pinjaman) belaka. Ia harus lahir dari analisis yang transparen, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan memertimbangkan skenario pembanding secara serius.
Indonesia kini berada di persimpangan jalan: apakah kita akan melompat ke teknologi berisiko tinggi dengan kesiapan yang belum matang, atau membangun fondasi energi bersih dari sumberdaya yang telah kita miliki berlimpah, sambil memersiapkan diri secara bertahap jika suatu hari nuklir benar-benar menjadi pilihan yang tak terhindarkan? Jawaban atas pertanyaan penting ini akan memengaruhi bukan hanya bagaimana kita menyalakan lampu dan mesin di hari ini, tetapi bagaimana kita menjaga agar cahaya itu tetap menyinari dan menggerakkan masa depan tanpa membakar generasi yang akan datang.

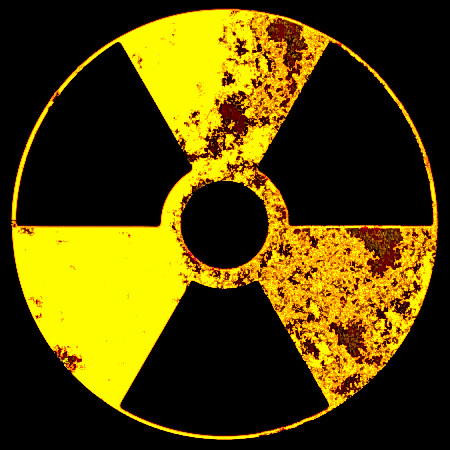





Leave A Comment